Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn.
Anggota DPR RI, Komisi II
Pemerintah akhirnya sadar selama ini telah abai pada amanat Ketetapan MPR Nomor IX /2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Kesadaran itu ditunjukkan dengan mengganti Kepala BPN beberapa waktu lalu, dan Presiden secara khusus meminta Kepala BPN yang baru memrioritaskan pembaruan agraria berupa redistribusi tanah pertanian untuk rakyat kecil, selain penyelesaian masalah konflik dan sengketa pertanahan.
Rencana Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang hendak memetakan konflik-sengketa pertanahan di seluruh Indonesia dalam bulan pertama patut didukung. Kemudian dalam waktu seratus hari ke depan sudah ada beberapa yang terselesaikan-terutama terhadap yang berskala besar. Hal yang sama diberlakukan terhadap redistribusi yang akan diambil dari tanah/lahan terlantar, atau yang nyata-nyata tidak dipergunakan sesuai peruntukannya. Fungsi sosial tanah (vide; pasal 6 dan Penjelasannya), semestinya membawa manfaat bagi kesejahteraan.
Konflik dan sengketa pertanahan mulai menjadi perhatian serius pemerintah, setelah serangkaian peristiwa tragis terkuak di beberapa tempat, dalam skala masif dan menimbulkan banyak korban. Konflik-sengketa muncul antara lain menyangkut tanah hukum adat. Selama ini pemerintah sering menempuh jalan paradoksal, di satu sisi mengakui keberadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide; UUPA pasal 3, dan pasal 18 B ayat 2 UUD 1945),
di lain sisi dalam prakteknya justru dihambat oleh peraturan dibawahnya (vide; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5/1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat).
Instansi pemerintah yang lain juga mempunyai sudut pandang berbeda, contoh seperti Kementerian Kehutanan yang membuat kriteria tersendiri mengenai masyarakat hukum adat – sebagai subjek tanah hak ulayat. Demikianpun Kementerian Pertanian dengan UU Nomor 18/2004 (vide; Penjelasan pasal 9 ayat 2), UU Nomor 7/2004 tentang sumber daya air (vide; Penjelasan pasal 6 ayat 3), UU Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(vide; pasal 1 angka 31).

Sejarah konflik pertanahan, biasanya memang acap kali disulut rasa keadilan yang terkoyak oleh timpangnya struktur penguasaan, dan tumpang tindihnya berbagai kebijakan dan peraturan yang tidak membawa kemakmuran masyarakat. Padahal konsepsi hukum tanah nasional berasal dari alam pemikiran hukum adat budaya bangsa, terkait hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah ulayatnya. Ini adalah idiologi asli bangsa Indonesia yang menempatkan keseimbangan kosmis antara kepentingan bersama dan kepentingan individu. Dalam bahasa falsafah negara Pancasila, konsepsi ini memposisikan seseorang dengan masyarakatnya secara selaras, serasi, dan seimbang. Karena itu segala kebijakan pertanahan nasional, selayaknya dilakukan dengan tetap mempertahankan konsepsi yang digali dari akar budaya bangsa tanpa menutup diri terhadap perubahan zaman.
Pasal 33 UUD 1945
UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam pasal 1, menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Artinya, sekalipun tanah merupakan hak bersama bangsa Indonesia (terdapat unsur perdata), tetapi ia tidak sepenuhnya menjadi hak dari para pemiliknya dan oleh sebab itu mengandung unsur publik (tugas kewenangan). Hubungan
demikian seperti hubungan hak ulayat sehingga tidak dalam pengertian hubungan milik, namun menempati posisi teratas yaitu pada tingkatan seluruh wilayah nusantara.
Tugas kewenangan tersebut dilaksanakan oleh negara melalui hak menguasai sebagaimana rumusan pasal 2 UUPA, dan merupakan tafsir otentik pengertian “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Makna ‘dikuasai’ oleh negara berbeda dengan ‘dimiliki’ sebagaimana diartikan dalam domain negara pada masa kolonial. Kelahiran UUPA adalah bagian dari keberhasilan bangsa untuk melepaskan diri dari keterikatan pada peraturan hukum kolonial, dan juga mengakhiri dualisme hukum barat dan hukum adat. Maka menjadi wajar jika negeri Indonesia yang agraris menganggap bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan, mempunyai fungsi yang amat vital untuk membangun masyarakat adil-makmur.
Dalam praktek, pejabat pemerintah menafsirkan tanah dikuasai negara sebagai hak milik negara (seperti zaman penjajahan). Maka tidak heran konflik-sengketa tanah hak ulayat selalu terjadi. Domain-Verklaring ternyata tidak hapus melainkan bermetamorfosa menjadi hak milik negara. Ini sungguh merupakan pelecehan terhadap pasal 33 UUD 1945, karena frase, ‘dikuasai oleh negara’ mustinya diteruskan secara lengkap dengan frase ‘dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Karena penguasaan tanah oleh negara atau hak milik negara tidak identik dengan pemilikan, maka tanah rakyat (ulayat) yang telah dibuatkan sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) oleh oknum pejabat – dan diberikan kepada konglomerat, misalnya, tidak boleh dimaknai sebagai tidak lagi bisa dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik sah.
Ketetapan MPR RI Nomor IX/2001, tentulah dilatar belakangi keprihatinan mendalam dan pertimbangan mendasar. Pengelolaan pertanahan selama ini dianggap telah merusak kualitas lingkungan hidup, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya yang menimbulkan berbagai konflik. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan nyata demi terciptanya pemeratan pemanfaatan sumber daya, dan menjamin keadilan dan kemakmuran rakyat.
Jika saja pemerintah sejak awal serius menjalankan Tap MPR, tentulah soal sengketa tanah dapat diredam. Karena Tap ini sebenarnya meminta kembali pelaksanaan UUPA secara benar dan konsekuen, seperti program land-reform dengan resdistribusi tanah bagi rumah tangga petani yang tidak memiliki lahan pertanian. Konon pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang reforma agraria, tetapi hingga saat ini tidak terdengar kabarnya. Pemerintah lupa pada tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan melaksanakan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.
Hilangnya otonomi daerah
Pemerintah kemudian menerbitkan Keppres tahun 2003 pasca Tap MPR Nomor IX/2001, diantaranya mengatur kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan UU Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pertanahan. Sejalan dengan UUPA yang jelas menetapkan wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah di daerah yang bersangkutan. Tetapi (sayang), berseberangan dengan ketentuan ini,
BPN berdiri tegak di setiap provinsi, kabupaten dan kota yang terpisah dari pelayanan publik lain.
BPN semakin memperoleh legitimasi dengan diterbitkannya Perpres Nomor 10/2006, menyebutkan bahwa tanah merupakan perekat NKRI sehingga perlu diatur dan dikelola secara nasional. Perpres ini mengobrak-abrik desentralisasi pertanahan model otonomi daerah, padahal prinsip otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32/2004, ialah menekankan perwujudan otonomi seluas luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Artinya, daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter-fiskal nasional, dan agama. Tidak ada di dalamnya urusan pertanahan. Pembagian urusan didasarkan pada pemikiran, bahwa akan selalu ada banyak urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pusat, karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Perpres Nomor 10/2006, seperti mau melawan UUD 1945. Dalam Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat (5) menjelaskan, bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Re-sentralisasi?
Kondisi demikian, menggambarkan pemerintahan sekarang meneruskan pola kebijakan pertanahan era orde baru, pelan dan pasti mengarah pada re-sentralisasi. Sejarah mencatat ketika terjadi peralihan dramatis dari kepemimpinan Soekarno kepada Soeharto, telah membawa perubahan radikal pada kebijakan pertanahan. Kementerian Agraria dihapus dan UUPA tidak lagi menjadi induk dari peraturan perundangan, maka tahun 1967 lahirlah UU tentang PMA (Penanaman Modal Asing) dan UU tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Siapapun dapat bersaksi, hingga kini kebijakan pertanahan sepertinya tidak bebas merdeka dari pengaruh dan kepentingan pihak asing. Hilang sudah semboyan “Tri Sakti”, yaitu berdaulat dalam politik, berdikasi di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
Selama tiga dekade pemerintahan orde baru, investasi besar seperti mining industry, forest dan agro industry telah merasuk jauh ke dalam sistem ekonomi. Strategi pembangunan yang mengundang masuknya multi national corporation (MNC) menyebabkan kebijakan pertanahan (dan agraria pada umumnya) tersandera pada kepentingan ekonomi internasional. Indonesia dengan sadar masuk dalam rezim perdagangan bebas dunia seperti AFTA, APEC, WTO dan
ikut menandatangani General Agreement on Trade and Tariff (GAAT). Dampak yang ditimbulkan dari industri industri besar tersebut luar biasa buruk, sebagaimana diurai dalam pertimbangan Tap MPR, diantaranya ialah timpangnya susunan penguasaan tanah dan mengakibatkan banyak konflik. Ketetapan MPR Nomor IX/2001 sejatinya menggiring orientasi kebijakan pertanahan kembali ke “khittah” UUPA. Selain itu Tap ini juga menjalankan tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar pembangunan nasional dalam menjawab reformasi berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat, serta kerusakan sumber daya alam.
Di tengah kondisi objektif timpangnya struktur penguasaan tanah, rusaknya lingkungan hidup. bumi makin panas dan hutan gundul akibat musnah ditebas, maka pembaruan agraria merupakan keniscayaan.
RUU Pertanahan
Salah satu tujuan dalam RUU Pertanahan adalah menyangkut upaya penyempurnaan ketentuan peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan pembaruan agraria. Rancangan UU ini masih jabang bayi dan sangat prematur. Karena itu memerlukan daya upaya lebih berbagai pihak, untuk memberikan masukan, saran dan kritik. Bagaimanapun, semangat reformasi sesuai Tap MPR Nomor IX/2001 harus tetap menggelora. Beberapa catatan penting untuk diwacananakan antara lain, pertama, bagaimana RUU Pertanahan tidak sekedar mengatur hak-hak atas tanah melainkan juga menjabarkan prinsip umum UUPA, misalnya terhadap jaminan setiap orang mempunyai hak atas tanah (pasal4). Catatan selanjutnya adalah bagaimana memmrioritaskan WNI yang belum memiliki hak atas tanah (pasal9); fungsi sosial (pasal6) meliputi larangan terlantarkan tanah, dan larangan menjadikan tanah sebagai spekulasi komoditi; sosialisme Indonesia (pasal 7 dan 17) semangat pemerataan melalui penentuan batas maksimum pemilikan tanah.
Kedua, pengaturan ‘hak menguasai negara’ antara (pemerintah) pusat dengan daerah agar jelas status dan kewenangan otonomi daerah – bagaimana tidak kembali ke arah sentralisasi. Juga ihwal pengertian dan pengaturan ‘tanah negara’ lebih lanjut. Ketiga, mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih simpang siur agar lebih dipertegas, dengan ini setidaknya dapat mengurangi konflik dan sengketa. Demikian juga mengenai Hak Pengelolaan yang tidak jelas jenis kelaminnya, dalam RUU ini berpotensi menjadi hak eigendom partikelir seperti zaman kolonial (pasal 1 RUU bertolak belakang dengan pasal 9 ayat 3). Keempat, menyangkut redistribusi tanah yang tidak lepas dari kemauan politik pemerintah terhadap land-reform (UU/Perppu Nomor 56/1960), lebih dipertegas pengaturannya dalam RUU ini.
Kelima, bagaimana mengatur PPAT lebih lanjut ke dalam (rancangan) undang-undang ini. UUPA hanya memerintahkan mengenai pendaftaran tanah diatur dengan PP, dan dari PP nomor 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah lahirlah Peraturan Menteri Agraria Nomor 10/1961 mengenai penunjukan pejabat yang dimaksud dalam pasal 19 PP Nomor 10/1961 tentang pendaftaran tanah serta hak dan kewajibannya. Keberadaan pejabat tersebut kemudian memperoleh pengukuhan dalam UU nomor 16/1985 tentang Rumah Susun, sebelum akhirnya dikeluarkan PP Nomor 37/1998 tentang PPAT. Mungkin perlu lebih dikukuhkan lagi ke dalam RUU Pertanahan agar tidak terjadi tumpang tindih tata urutan perundangan dan terpenting dapat disesuaikan dengan amanah Tap
MPR IX/2001.
Tulisan ini disampaikan pada Seminar Nasional Pertanahan 2012, PP IPPAT-Universitas Jayabaya





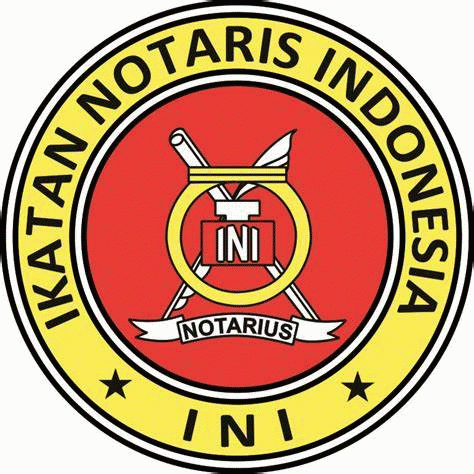


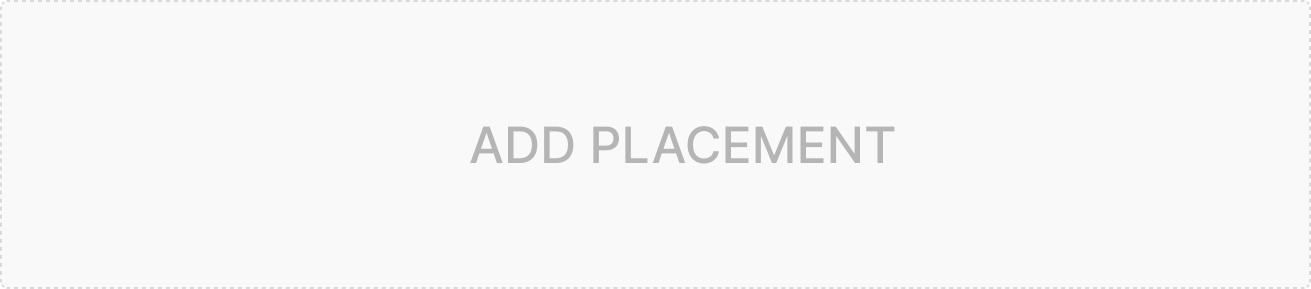
Tinggalkan komentar