PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
Oleh :
Prof.Dr.H.Muladi,SH
Dr.Diah Sulistyani Muladi,SH,CN,M.Hum. (Liezty Muladi)
“It is truly said that a corporation has no conscience; but a corporation of conscientious men is a corporation with a conscience” (Thoreau, 1983)

A. Riwayat Hidup Penulis : Prof.Dr.H.Muladi,SH.
Prof.Dr.H.Muladi,SH, lahir di Surakarta, pada tanggal 26 Mei 1943, mantan Komandan Batalyon Resimen Mahasiswa untuk Penumpasan G-30 S–PKI waktu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Alumni KSA III LEMHANNAS RI tahun 1993, kedudukan yang pernah dijabat antara lain :
– Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1986-1992);
– Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (1992-1994);
– Rektor Universitas Diponegoro (1994-1998);
– Anggota Komnas HAM (1993-1998);
– National Correspondent RI pada Commission of Crime Prevention and Criminal Justice, ECOSOC PBB (1992-1998);
– Anggota MPR-RI Utusan Daerah Jawa Tengah, Sekretaris Panitia Ad Hoc II (1994-1998);
– Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan VII ( 1998);
– Menteri Kehakiman Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999) merangkap sebagai Menteri Sekretaris Negara Kabinet Reformasi Pembangunan (1999) merangkap Jaksa Agung;
– Hakim Agung (2001-2002);
– Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI (Gubernur LEMHANNAS RI ) kedudukan setingkat Jabatan Menteri (2005-2011);
B. Riwayat Hidup Penulis : Dr.Diah Sulistyani Muladi,SH,CN,MHum
1. Notaris-PPAT di Jakarta Barat.
2. Pejabat Lelang Kelas 2 (dua) di DKI Jakarta.
3. Dosen S1 dan S2 di Universitas Semarang (Yayasan Alumni UNDIP , sejak tahun 1995 sampai sekarang).
4. Dosen di Universitas Pancasila di Jakarta.
5. Dosen Magister Hukum di Universitas Jayabaya.
6. Dosen Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya.
7. Dosen Magister Kenotariatan di Universitas Brawijaya Malang.
8. Dosen Magister Kenotariatan di UNTAG Semarang.
9. Pernah menjadi Narasumber dan Dosen di Lemhannas RI, KEMHAN,POLDA, MABES TNI, dan berbagai macam seminar-seminar sampai sekarang.
10. Mengajar di diklat-diklat bank-bank di Jakarta dan mengajar di berbagai universitas negeri dan swasta serta aktif membuat tulisan-tulisan di media massa dan media on line.
Dan selain aktif di bidang akademisi dan praktisi, juga aktif sebagai Pengurus di Partai dan Ormas antara lain :
1. Ketua Badan Advokasi,Hukum dan HAM (BAKUMHAM), DPP KOSGORO 57 di Jakarta.
2. Sekjen Badan Advokasi ,Hukum dan HAM, DPP Partai GOLKAR di Jakarta.
3. Pengurus Pusat Departemen Hukum dan HAM , DPP Partai GOLKAR.
4. Pendiri Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI).
5. Salah satu Ketua dan Dewan Pakar di Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI).
6. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI).
7. Ketua Alumni Kenotariatan Universitas Diponegoro (IKANOT UNDIP).
8. Pengurus IKATAN ALUMNI (IKAL) PPSA 17 LEMHANNAS RI bidang Hukum.
9. dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya.
Prof.Muladi dan putrinya, Dr.Diah Liezty ini, menulis buku yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dimana Prof.Muladi menyoroti aspek pidana sedangkan Dr.Diah Liezty memberikan masukan dari aspek perdata dari kejahatan Korporasi. Berikut ini adalah oto-resensi buku tersebut.

Buku tersebut mengupas perihal kejahatan ekonomi (economic related crimes) berupa kejahatan korporasi (corporate crimes), baik yang merupakan “crimes for corporation” maupun “corporate criminal” (corporatie’s misdaad). Kejahatan korporasi tidak termasuk di dalamnya “crimes against corporation”, yang berorientasi pada kepentingan individual yang merugikan korporasi. Dengan kata lain “corporate crimes are offences committed by corporate officials for their corporations and the offences of the corporation themselves for corporate gain” (Dunfee, 1998). Contoh penyuapan pejabat pemerintah, pencemaran lingkungan, penggelapan pajak, produksi yang membahayakan konsumen, persaingan usaha yang tidak fair, dll. Bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi yang dilakukan oleh “non-state actors” memang tidak bersifat “state centric security threat”, tetapi merupakan bahaya terhadap “human security”, baik individul, kelompok maupun masyarakat. Dalam hal ini kemungkinan yang dapat menjadi korban kejahatan korporasi adalah : perusahaan saingan (spionase industri, persaiangan yang tidak jujur), Negara (penggelapan pajak) , karyawan (lingkungan kerja yang tidak sehat), konsumen (produksi makanan beracun) , masyarakat (kejahatan lingkungan) dan pemegang saham yang tidak bersalah.
Perlu dicatat bahwa sekalipun kejahatan ekonomi pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan (non-violent crimes), namun selalu disertai dengan kecurangan (deceit), penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (concealment of facts), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal-akalan (subterfuge) dan pengelakan peraturan (illegal circumvention), untuk membedakannya dengan kasus perdata dan administratif.
Yang ironis adalah, bahwa di kalangan bisnis terdapat budaya “anomie of success” yang mengandung makna bahwa kejahatan korporasi diyakini sebagai perilaku rasional yang dapat menghalalkan segala cara atas dasar prinsip ekonomi untuk mengembangkan keuntungan bisnis dan apabila terpaksa melanggar hukum dipertimbangkan sebagai “unfortunate mistakes” yang diyakini tidak akan mengandung stigma sosial di lingkungannya. Dari sisi tujuan pemidanaan hal ini berseberangan dengan tujuan yang bersifat “dissuasive” atau menimbulkan jera.
Istilah lain yang digunakan iuntuk kejahatan korporasi adalah “crime in the suites” (illegal acts by a corporation or top officials), untuk merefleksikan kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi yang merugikan Negara, korporasi lain atau masyarakat, yang berseberangan dengan “crimes in the street” (perampokan , perkosaan, narkoba) dan “white collar crimes” yang secara luas juga dilakukan untuk merugikan perusahaan dan perseorangan untuk kepentingan pribadi (occupational crimes). Contoh kejahatan korporasi secara umum adalah “bribery, ,kickbacks, illegal rebates, price-fixing, bid-ridging, unfair competitive practices, tax evasion, environmental pollution, illegal political contribution, discriminatory employment practices, product pirating and counterfeiting, and sale of unreasonably dangerous products”.
Yang menarik adalah, berbeda dengan “crimes in the street” yang dianggap “malum in se” yang bersifat “naturally wrong” seperti perampokan, pencurian, kekerasan dll. , pada mulanya kejahatan korporasi merupakan “malum prohibitum” (they are considered wrong because a statute defines them to be so”.
Atas dasar kerangka berfikir yang lain juga disadari apabila ada yang menyatakan bahwa “corporate crime is The Untold Story” atau “quiet acts”, sebab secara individual korban dari kejahatan korporasi tidak merasakan menjadi korban, misalnya para konsumen yang tidak merasakan sebagai korban persaingan usaha yang tidak adil seperti “price fixing” walaupun secara kumulatif kuntungan korporasi sangat besar. Demikian juga korban polusi lingkungan secara individual tidak merasakan, padahal secara keseluruhan dampaknya multidimensional baik secara ekonomis, sosial, fisik maupun lingkungan hidup.
Lebih-lebih seringkali karena dianggap sebagai masalah hukum perdata dan administrative, atas dasar prinsip “ultimum remedium” atau asas subsidiaritas jarang sekali diterapkan pidana penjara. Di samping itu biaya penegakan hukum kejahatan korporasi sangat besar dan kompleks serta memakan waktu lama dan pasti tidak menarik liputan mass media. Korban juga sering tidak tahu siapa yang harus disalahkan.
Salah satu fenomena yang menarik di Indonesia adalah jarang diterapkannya pemidanaan terhadap korporasi, padahal syarat-syarat pemidanaan sudah memadai dan perundang-undangan sangat mendukung. Contoh tindak pidana korupsi yang mulai dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Demikian juga dengan kejahatan lingkungan hidup.
Beberapa kemungkinan yang terjadi sebagai alasan adalah masalah kualitas profesionalisme penegak hukum yang kurang memahami kejahatan korporasi, masalah pembuktian yang kompleks dan adanya kenyataan bahwa kejahatan korporasi merupakan “crime by powerful” baik politik maupun ekonomi sehingga menimbulkan sluggish dalam penegakan hukum.
Perkembangan kejahatan korporasi di Indonesia cukup menarik, karena pengertian korporasi tidak hanya berkonotasi ekonomis berupa kumpulan kekayaan yang terorganisasi berupa badan hukum (legal person /legal entity) , tetapi juga dapat berupa kumpulan orang (natural person) dan kekayaan yang terorganisasi yang tidak merupakan badan hukum. Hal ini memungkinkan untuk memperluas kejahatan korporasi sehingga dapat diterapkan juga terhadap organisasi kejahatan (mis. terorisme, human trafficking) .
Dalam kaitannya dengan korporasi, suatu organisasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan karyawannya, wakil perusahaannya, atau mereka yang memperoleh mandat dari perusahannya, atau setiap orang yang bertanggungjawab kepadanya. Semula hal ini khusus diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan yang masuk kategori ‘absolute liability offences’. Keragu-raguan ini didasarkan atas pemikiran bahwa teori ini bertolak belakang dengan apa yang dinamakan ‘the docftrine of mens rea’ yang menekankan pada unsur kesalahan subyektif orang.
Teori Identifikasi (Identification Theory) hampir lebih dari satu abad dipergunakan dalam pengadilan Inggris. Atas dasar teori ini, maka semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasikan dengan organisasi atau mereka yang disebut ‘who constitute its directing mind’, yaitu individu-individu seperti para pejabat atau pegawai yang mempunyai tingkatan manager, yang dalam tugasnya tidak di bawah perintah atau arahan dari kewenangan atasan yang lain dalam organisasi, dapat diidentifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian pertanggungjawaban korporasi tidak didasarkan atas tanggungjawab pengganti (vicarious liability).
Dalam hal ini persoalan akan timbul apabila korporasi tersebut sangat besar dengan pusat-pusat pengambilan keputusan yang ‘fragmented’. Sehubungan dengan hal ini Canada mengadopsi teori ini dengan modifikasi atas dasar Teori Delegasi (the Delegation Theory). Melalui teori ini, lingkaran individu yang harus bertanggungjawab diperluas dan mencakup pula gabungan para ‘board of directors, managing director, the superintendent’, manager dan setiap orang yang memperoleh delegasi dari ‘board of directors’ untuk meleksanakan kewenangan korporasi.

Dengan demikian setiap perbuatan dari gabungan tersebut juga merupakan perbuatan korporasi. Dengan demikian ada kemungkinan suatu korporasi memiliki lebih dari satu ‘directing mind’, di samping ‘corporate centre’, atas dasar delegasi wewenang atau sub-delegasi wewenang dari pusat korporasi atas dasar prinsip desentralisasi. Perkembangan ini bisa dikatakan merupakan jalan tengah antara teori identifikasi dan ‘vicarious liability’ yang luas.
Iacobucci (2000) memberikan beberapa kategori tentang parameter apa yang dinamakan kewenangan untuk menentukan ‘the notion of directing mind’ sebagai berikut :
• Kewenangan pengambilan keputusan dalam aktivitas korporasi yang relevan, termasuk kewenangan untuk mendesain dan mengawasi implementasi kebijakan korporasi;
• Kapasitas untuk melakukan pengambilan keputusan dalam kerangka kebijakan korporasi, lebih dari sekedar memberikan effek kebijakan secara operasional, baik di kantor pusat maupun di pelbagai cabang;
• Penentuannya harus didasarkan atas pendekatan kasus per kasus (case by case analysis);
• Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan selama orang yang melakukan tindak pidana tidak memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan korporasi yang harus dilaksanakannya ;
• Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, bilamana orang yang memiliki ‘directing mind’ tersebut terlibat dalam kecurangan (fraud) korporasi, sedangkan korporasi sama sekali tidak memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut (crimes against corporation).
KEJAHATAN KORPORASI DAN ‘WHITE COLLAR CRIME” (WCC)
Secara teoritik dan konseptual, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat (WCC) mencakup pula kejahatan korporasi. Yang terakhir ini menggambarkan suatu bentuk kejahatan yang bersifat luas yang tidak terkait dengan kejahatan biasa (ordinary crimes) seperti perampokan, penyerangan, pencurian dan sebagainya. Dua kategori kejahatan tersebut berbeda baik di dalam hakikat maupun situasi di mana kejahatan tersebut terjadi, dan sanksi yang diterapkan lebih banyak bersifat administratif dan perdata daripada bersifat sanksi pidana, sekalipun dalam perkembangannya sanksi pidana juga dikembangkan.
Sekalipun ‘WCC’ pada umumnya melibatkan perbuatan yang melawan hukum yang bersifat finansial, kejahatan ini biasanya juga disertai dengan kerugian baik potensial maupun aktual atau bahkan akibat berupa kematian. Sebagai contoh tindak pidana lingkungan hidup (eco-crime), perlindungan kerja dan perlindungan konsumen yang kurang baik, penjualan obat –obatan yang tidak bertanggungjawab dan lain-lain.
Kejahatan korporasi, seperti halnya ‘WCC’ yang merupakan salah satu bagiannya, merupakan suatu perbuatan yang diancam pidana oleh Negara, tanpa menghiraukan apakah akan dijatuhi sanksi administratif atau sanksi perdata seperti lazimnya atau sanksi pidana. Secara khusus kejahatan korporasi mengandung makna sebagai perbuatan suatu korporasi, atau individu yang bertindak atas nama korporasi, yang dilarang oleh undang-undang. (Braithwaite, 1992)
Para kriminolog mulai mengembangkan perhatian terhadap WCC, dan khususnya kejahatan korporasi, setelah Sutherland mengucapkan pidatonya di depan ‘the American Sociological Society’ pada tahun 1939. Riset yang dilakukannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 70 korporasi non-finansial terbesar menghasilkan antara lain perluasan definisi kejahatan di luar hukum pidana dan mencakup perbuatan-perbuatan yang dipidana secara administratif dan secara perdata.
Dengan berkembangnya gerakan-gerakan perlindungan konsumen pada tahun 70-an, berbagai riset tentang WCC, korban WCC dan aspek system peradilan pidana WCC banyak dilakukan. Namun selama pendekatan yang dilakukan masih bersifat individualistik (individualistic approach) hasilnya tidak akan memuaskan karena apa yang terjadi justru merupakan ‘illegal bahavior of an organization’ seperti yang terjadi di suatu korporasi yang besar.
WCC bisa bersifat okupasional, atau mungkin organisasional. Yang pertama terdiri atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok kecil dalam kaitannya dengan jabatannya atau pekerjaannya, seperti yang dilakukan oleh dokter, ahli farmasi, advokat, notaris, pengusaha kecil dan sebagainya.
Dalam bisnis hal ini bisa berupa penghindaran pajak, penggelapan, manipulasi, para pejabat pemerintah dan politisi banyak yang melakukan misalnya penggunaan dana publik secara melawan hukum, ‘money politics’, pengecualian pajak secara melawan hukum, dokter melakukan praktek aborsi, advokat membantu memberikan kesaksian palsu dan notaris turut serta memberikan keterangan plasu dalam pembuatan aktanya dan lain-lain, yang sering disebut sebagai “professional fringe violator”.
Di samping WCC yang bersifat individual, kejahatan organisasional (organizational crime) merupakan bentuk khusus dari WCC. Dalam hal ini organisasi atau kelompok mengkoordinasi usaha untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif seperti yang dilakukan oleh suatu perusahaan besar atau organisasi pekerja. . Hal ini sulit dijelaskan tanpa melihat organisasi sebagai sistem sosial. Yang kedua adalah kenyataan bahwa komponen esensial dari perkembangannya adalah pengakuan bahwa baik organisasi maupun individul melakukan kejahatan untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam proses pengambilan keputusan yang normal.
Fokus pada tujuan merupakan karakteristik sentral dari organisasi sehingga disebut ‘organiszational crime’. Standar evaluasi kesuksesan tergantung dari keberhasilan untuk mencapai tujuan ini. Untuk itulah peranan struktur sosial dalam organisasi penting seperti penentuan tujuan, proses-proses internal, keberadaan hierarkhi dan antar hubungan di dalamnya yang bersifat sistemik yang secara keseluruhan menyebabkan perilaku yang melawan hukum. Staf organisasi dalam melakukan aktivitas yang menyimpang dan bersifat melawan hukum mendayagunakan keahliannya, pengetahuannya dan pelbagai sumber yang tersedia melengkapi okupasi mereka. Kejahatan organisasional terjadi dalam kerangka pekerjaan dan dilakukan oleh mereka yang berperan serta dalam organisasi. Dalam hal ini WCC merupakan kejahatan korporasi (crimes for corporation), bukan “crimes against corporation”. Contoh : fraud, bribery, ponzi schemes, insider trading, embezzlement, cybercrime, copyright infringement, money laundering, identity theft an forgery”.
Di abad modern ini, kejahatan korporasi bahkan melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional (MNC). Mereka tidak hanya memproduksi barang-barang dalam skala besar, tetapi juga mendomisasi ekonomi dunia, mempekerjakan jutaan orang, dan mempengaruhi pilihan-pilihan konsumen melalui pendayagunaan teknologi canggih. Berbagai data membuktikan bahwa pararel dengan kekuatan produksi di atas, muncul pula perilaku yang tidak bertanggungjawab yang secara aktual dan potensial bisa merugikan masyarakat, konsumen, Negara, perusahaan kompetitor dan karyawan sendiri dalam skala besar. Contohnya adalah advertensi yang tidak sesuai dengan kenyataan, memasarkan hasil produksi yang tidak aman, polusi lingkungan, penyuapan politik, korupsi komersial (foreign payoff), penghindaran pajak, produksi barang-barang beracun, pemalsuam data perusahaan yang merugikan pemegang saham, aspiionase industri, kejahatan atas hak milik intelektual dan sebagainya. Perilaku mereka jauh dari ketaatan terhadap etika bisnis. Bahkan tidak jarang MNC terlibat dalam pelanggaran HAM yang terjadi di suatu Negara yang dikuasai oleh suatu rezim otoriter.
Dengan demikian jelas betapa berbahayanya WCC organisasional dan kejahatan korporasi, sehingga sangat realistik apabila terjadi peningkatan kriminalisasi dalam arti luas untuk menghadapinya. Semakin besar suatu korporasi dengan difusi tanggungjawab dan struktur yang kompleks, hal ini turut mendorong perkembangan kejahatan korporasi. Secara umum hal-hal lain yang mempengaruhi adalah kualitas ‘top management’, kompetisi yang tidak sehat, tipe industri, riwayat korporasi di bidang etika, persoalan finansial di dalam korporasi, sejarah korporasi terhadap ketaatan hukum dan sebagainya. Dalam hal ini secara keseluruhan peranan organisasi dan ‘collecivities of discrete individuals’ sangat strategis.
Perilaku korporasi yang melawan hukum adalah bentuk dari pelanggaran hukum kolektif dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional, melalui perilaku sekelompok manusia yang terorganisasi dalam suatu tujuan bersama. Hal lain yang turut berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan tersebut adalah kultur lingkungan sosial yang kondusif, tekanan-tekanan serta pengawasan internal dan eksternal yang lemah, reaksi sosial yang kurang serta penegakan hukum yang relatif tidak tegas.
Pada saat dirumuskan, para penyusun WvS (KUHP) 1886 menerima asas “Societas/universitas delinquere non potest” yang artinya adalah bahwa badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana. Hal ini merupakan reaksi terhadap praktek-praktek kekuasaan yang absolut sebelum Revolusi Perancis 1789, yang memungkinkan terjadinya “collective responsibility” terhadap kesalahan seseorang. Dengan demikian menurut konsep dasar KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (natuurlijke persoon). Dalam hal ini terkandung 2 (dua) hal yakni. (1) hal apakah korporasi dapat melakukan tindak pidana; dan (2) hal dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi, apakah pidana dan/atau tindakan.(Sudarto, 1981).

Prinsip ini secara tersurat dan tersirat tercantum dalam Pasal 51 (lama) Wetboek van Strafrecht Belanda atau Pasal 59 KUHP Indonesia yang berbunyi :
“Jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidaklah dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena salahnya.” Baik Aliran Klassik (Daad-Strafrecht), Aliran Modern (Dader-Strafrecht) maupun Aliran Neo-Klassik (Daad-daderstrafrecht) melihat individu sebagai pelaku atau subyek hukum sentral.(Muladi, 1984).
Dalam perkembangannya kemudian timbul kesulitan dalam praktek, sebab di dalam pelbagai tindak pidana khusus di luar kodifikasi/KUHP timbul perkembangan yang pada dasarnya menganggap bahwa tindak pidana juga dapat dilakukan oleh korporasi, mengingat kualitas keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum atau korporasi. Hal ini dimungkinkan atas dasar Pasal 91 KUHP Belanda atau Pasal 103 KUHP Indonesia yang memungkinkan peraturan di luar kodifikasi menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I. Contoh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pemberantasan Terorisme, UU Tentang Lingkungan Hidup, UU Pencucian Uang, UU Pengadilan HAM dll.
Perkembangan hukum positif di Indonesia menampakkan hal-hal yang sama, yaitu melalui 4 (empat) tahap perkembangan yang berkisar pada hal dapat dipidananya perbuatan oleh korporasi dan hal dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dan kemungkinan dapat dipidananya korporasi . Perkembangan pada Tahap I menunjukkan bahwa keduanya hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah; Pada perkembangan Tahap II korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia alamiah; dan dalam perkembangan Tahap III, baik manusia alamiah maupun korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipidana dalam tindak-tindak pidana tertentu dan Tahap IV adalah dalam RUU KUHP yang akan memasukkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Buku I KUHP dan berlaku untuk semua tindak pidana. Tahap III nampak antara lain dalam UU No. 11 PNPS 1963, UU No. 7 Drt. Th. 1955 (keduanya sudah dicabut), UU No. 31 Th. 1999. Jo. UU No. 20/2001, UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dll.
Perkembangan Tahap IV bersifat “ius constituendum” yang akan mengikuti apa yang terjadi di Belanda, yaitu melembagakan perkembangan yang ada di luar KUHP, dengan mengatur pertanggungjawaban korporasi secara umum dalam Buku I KUHP, sehingga berlaku untuk semua tindak pidana.
Di Belanda, pembicaraan korporasi sebagai subyek hukum (Normadressat) akan menyentuh persoalan utama yaitu kapan dan apa ukurannya untuk dapat mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Sekalipun ada pendapat bahwa hal ini harus diterapkan kasus per kasus (kasuistis) sesuai dengan sifat kekhasan delik tertentu (misalnya delik fungsional yang lebih bersifat administratif dan delik non- fungsional yang lebih bersifat fisik), namun sebagai pedoman dapat dikemukakan berbagai pemikiran sebagai berikut :
1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan hukum;
2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta dari badan hukum dan atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (bedrijfpolitiek), maka yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (feitelijkewerkzaamheden) dari badan hukum;
3. Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang -yang untuk pertanggungjawabannya dibebankan atas badan hukum- dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut;
4. Badan hukum baru dapat diberlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut “berwenang untuk melakukannya, terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan, dan di mana tindakan dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya “ dan “diterima atau biasanya diterima secara demikian” oleh badan hukum (Ijzerdraad-arrest HR. 1954). Syarat kekuasan (machtsvereiste) mencakup : wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan terlarang tersebut; mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang; Selanjutnya syarat penerimaan (akseptasi) (aanvaardingsvereiste), hal ini terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di dalam badan hukum dengan tindakan terlarang tersebut. Juga apabila ada kemampuan untuk mengwasi secara cukup. Hal ini menggambarkan bahwa Hukum Belanda telah bergerak cepat meninggalkan teori-teori tradisional tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti ‘vicarious liability’ dan ‘identification theory’. Kasus-kasus yang actual mendasarkan pertanggungjawaban korporasi pada prinsipnya pada 2 (dua) factor yaitu : (a) power of the corporation to determine which acts can be performed by its employees; dan (b) the acceptance of these acts in the normal course of business; Mahkamah Agung Belanda memutus bahwa perbuatan karyawan hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi apabila (a) perbuatannya dalam kerangka kewenangannya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan (b) perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang ‘accepted’ oleh perusahaan dalam kerangka operasionalisasi bisnis yang normal;
5. Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tertentu. (Torringa : Iklim psikis). Dalam kejadian-kejadian lain penyelesaian harus dilakukan dengan konstruksi pertanggungjawaban (toerekeningsconstructie) : kesengajaan dari perorangan (natuurlijk persoon) yang berbuat atas nama korporasi sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum tersebut;
6. Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum;
7. Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab dibagi; Demikian pula apabila berkaitan dengan masalah kealpaan;
8. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum;, bahkan sampai pada kesengajan kemungkinan;
Beberapa contoh pola pengaturan di Indonesia adalah sebagai berikut :
a. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
– Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
– Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;
– Dalam hal tindak pidana dilakukan atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
– Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
– Tuntutan pidana terhadap suatu korporasi, maka korporasi diwakili pengurus, yang juga dapat diwakili orang lain;
– Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3;
–
b. PERPU No. 2 Tahun 2002 jo. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
– Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun sipil yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;
– Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorgansasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
– Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama korporasi , maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
– Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
– Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
– Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak I triliun rupiah;
– Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang.
–
c. UU NJo. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
– Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;
– Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
– Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi;
– Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
– Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
– Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak seratus milliar rupiah;
– Selain pidana denda terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa : pengumuman keputusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; pencabutan izin usaha; pembubarn dan/atau pelarangan korporasi; perampasan asset korporasi untuk Negara ; dan/atau pengambilalihan korporasi oleh Negara.
d. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
– Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
– Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;
– Sanksi pidana terhadap badan usaha diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional;
– Pidana tambahan atau pidana tata tertib yang dapat dikenakan kepada badan usaha :
a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c) perbaikan akibat tindak pidana;
d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan /atau
e) penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama paling lama 3 tahun.
Catatan : Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sekalipun disinggung kemungkinan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tetapi tuntutan dan sanksi pidananya hanya dijatuhkan kepada pengurusnya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan tambahan 1/3 dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan apabila dikonstruksikan sebagai concursus realis (pendekatan multi-door) karena dianggap bukan lex specialis terhadap UU Lingkungan Hidup atau sebagai concursus idealis, ada atau tidak ada kaitannya dengan asas lex specialis derogat legi generali yang bersifat “systematische specialiteit”. Dalam hal ini secara yuridis atau sistematis suatu ketentuan pidana walaupun tidak memuat semua unsur dari ketentuan umum, tetap diangap bersifat khusus, apabila jelas dapat diketahui bahwa pembentuk UU memang bermakud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai ketentuan khusus.
e. UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
– Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
– Korporasi dikenai perrtanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam AD atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
– Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana : dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi;
– Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimun ditambah 2/3.
f. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
– Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
– Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi , selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya , pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali;
– Selain pidana denda korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; dan atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
g. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
– Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sesndiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
– Di samping pidana denda yang sangat berat dan bervariasi, terpidan pelaku usaha dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : pencabutan izin usaha; atau larangan kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain.
h. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
UU ini juga menentukan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum”. Namun sayangnya tidak diatur pertanggungjawban pidananya lebih lanjut al. tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum yang terlibat dalam tindak pidana intelijen.
Dalam kerangka langkah-langkah yuridis, sekalipun pada umumnya pendayagunaan hukum perdata dan hukum administrasi merupakan “primum remedium” dan hukum pidana sebagai “ultimum remedium”, namun diharapkan dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi dapat diutamakan.
PROSPEK PENGATURANNYA DI INDONESIA
Prospek pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia nampaknya cukup positif. Dalam RUU KUHP th. 2011 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, pertanggungjawaban korporasi tersebut akan diintegrasikan dalam Buku I KUHP (Ketentuan Umum) sebagaimana yang telah terjadi di Belanda pada tahun 1976. Dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RUU KUHP tersebut secara berturut-turut dirumuskan bahwa :
• Korporasi merupakan subyek tindak pidana; apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
• Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjkawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
• Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan ;
• Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi ;
• Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi ;;
• Pertimbangan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan dalam putusan hakim;
• Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi .
Catatan :
1) Dalam Pasal 205 RUU-KUHP ditegaskan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi”, sedangkan dalam Pasal 182 RUU-KUHP disebutkan bahwa “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan , baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;
2) Dalam Rancangan KUHAP yang saat juga sedang dipersiapkan oleh Kemenkumham, kiranya perlu pula disiapkan pengaturan tentang acara pidana yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang sudah dikenal didalam pelbagai pengaturan tindak pidana di luar KUHP. Hal ini pararel dengan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana yang diatur dalam RUU KUHP Buku I Tahun 2011.
Catatan :
Menurut Pasal 1653 KUH Perdata ‘badan hukum’ dibedakan menjadi :
a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah,
b. Badan hukum yang diakui, dan
c. Badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu.
Syarat materiilnya adalah : harus adanya kekayaan yang terpisah; mempunyai tujuan tertentu; mempunyai kepentingan sendiri; dan adanya organisasi yang teratur. Syarat formilnya adalah : harus memenuhi syarat yang ada hubungannya dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum ;
Dengan definisi ‘korporasi’ dalam RUU KUHP di atas, maka yang termasuk korporasi tidak hanya mencakup badan- badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi , atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, tetapi juga meliputi firms, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan yaitu badan-badan usaha yang berdasarkan hukum perdata, bukan suatu badan hukum.
Dengan mempertimbangkan betapa seriusnya kejahatan korporasi yang dapat mencakup berbagai kejahatan, baik kejahatan “mala prohibita “ maupun “mala per se”, maka agar lebih intensif dan efektif dalam penerapannya, dalam kerangka “ius constituendum” perlu diatur “Pedoman Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi “ dalam perundang-undangan, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil serta hukum pelaksanaan pidana. Hal ini dibutuhkan, karena dalam berbagai perundang-undangan hukum pidana yang mengatur kejahatan korporasi, perumusannya berbeda-beda, sehingga menimbulkan multi tafsir. Demikian pula tentang hukum acaranya, sehingga menimbulkan penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak pasti. Belum lagi hukum pelaksanaan pidananya.
Pedoman tersebut paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
1) Hakekat tindak pidana korporasi dan ruang lingkupnya;
2) Syarat pemidanan tindak pidana korporasi;
3) Ruang lingkup pemidanaan kejahatan korporasi;
4) Sanksi pidana dan tindakan yang dapat diterapkan;
5) Hukum acara yang berlaku bagi kejahatan korporasi;
6) Pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap kejahatan korporasi.
DAFTAR PUSTAKA.
Buci, P. Corporate Ethos : A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability, Minnesota Law Review, vo. 75, 1996
Box, Steven, Power, Crime and Mystification, Tavistock Studies in Sociology, Tavistock Public,. London, 1998.
Clapham, Andrew, Human Rights Obligations on Non-State Actors, Oxford University Press, 2006.
Coucil of Europe, Criminal Law Conventions on Corruption, 1998
Council of Europe, Civil Law convention on Corruption, 1988
Council of Europe Convention on Cybercrimes, 2001.
Clinnard, Marshall BH. & Yeager, Peter Clearly (2005), Corporate Crime , Somerset, NJ :Transaction Publishers.
Ferguson, Gerry, Corruption and Corporate Criminal Liability, paper on Seminar on New Global and Canadian Standards on Corruption and Bribery in Foreign business Transactions, Vancouver, BC, 1998.
Hanna, D, Corporate Criminal Liability, Criminal Law Quarterly, vol.31, 1989
Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Suatu pendekatan Terobosan Hukum melalui pendekatan Restoratif, R Media, Cetakan Pertama, 2008.
Moore, Magaldi & Gray, The Legal Environment of Business : A Contextual Approach, South Western Publishing Co., Cincinnati, 1997.
Muladi, Urgensi Revisi KUHAP di Masa Kini dan Paradigma yang melandasinya, makalah seminar Dirjen Pemasyarakatan – The AsiaFoundation, Jakarta, 10Mei 2011.
Remmelink, Jan, Hukum Pidana, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 (terjemahan)
Jonathan , Clough, “Not-so Innocents Abroad : Corporate Criminal Liablity for Human Rights Abuses”, (2005) Australian Journal of Human Rights 1; 2005 11 (1) AUJHR
Steiner, Henry J. and Alston, Philip, International Human Rights in Context, Clarendon Press, Oxford, 1996
Schaffmeister dkk., Hukum Pidana (terjemahan Sahetpy, JE), Konsorsium Iklmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyajarta, 1995
Tuohey, Mark, Corporate Criminal Liability in the US : Has Reform in the Law Brought Reform in the Boardroom ?, 2001
UNCAC, Merida Convention, 2003
US Institute of Peace Model Codes for Post Conflict Criminal Justice, http ://www.usip.org/model-codes-post-conflict-justice-/volume-2.
Wells, Cella, International Trade in Models of Corporate Liablity, paper presented at Conferences : University of Parma, 2000.







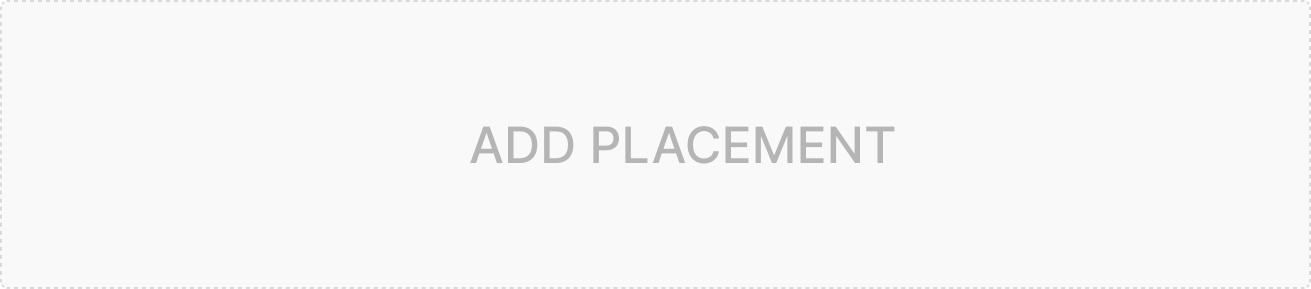
Tinggalkan komentar